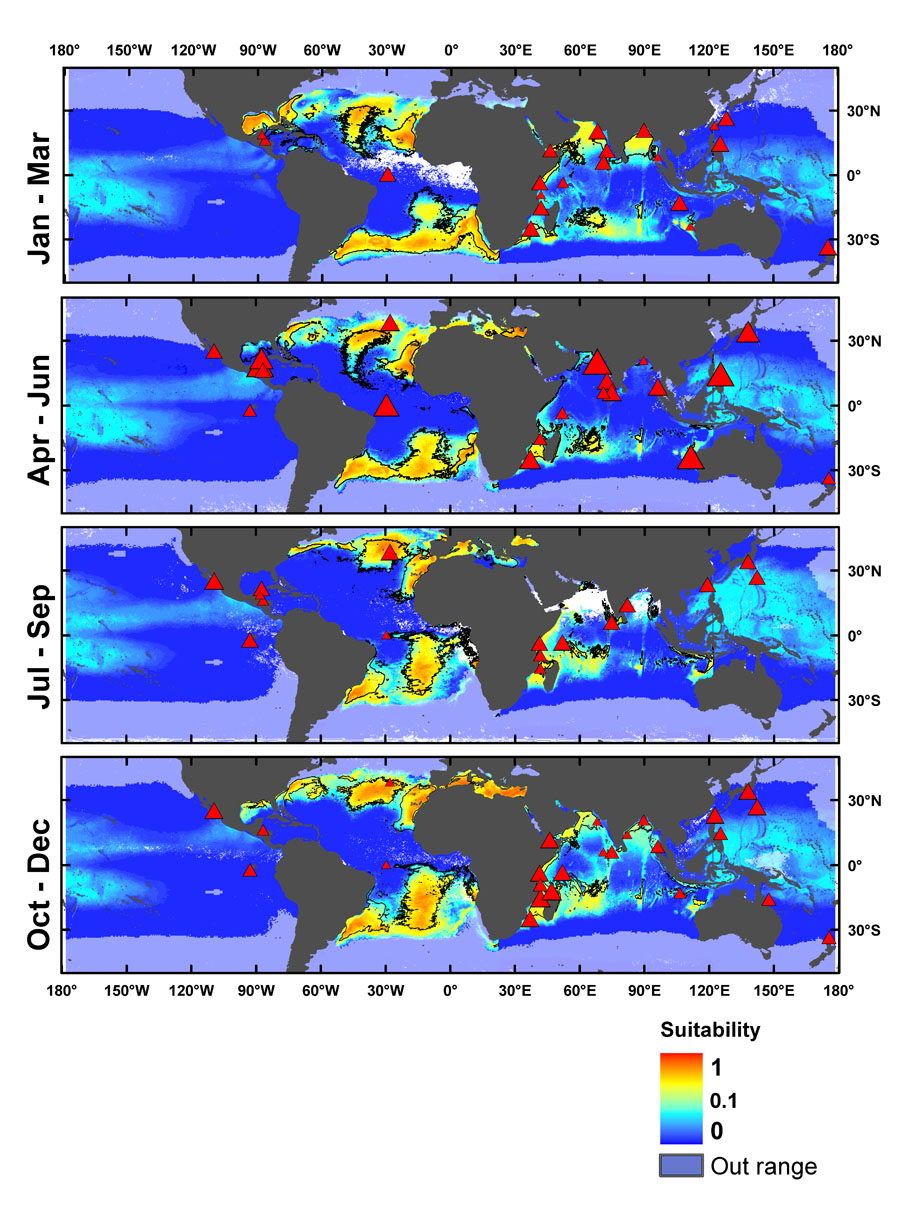![Pepohonan begitu padat di hutan adat Dayak Punan Adiu. Foto: Christopel Paino]()
Pepohonan begitu padat di hutan adat Dayak Punan Adiu. Foto: Christopel Paino
Malam itu, 15 Juni 2013. Bunyi mesin mobil memecah kesunyian Desa Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Markus Ilun segera keluar rumah. Sorot lampu mobil membuat silau mata. Empat orang turun dari mobil.
Markus, sang ketua adat, mencari tahu siapa mereka. Piang Irang, Kepala Desa Punan Adiu mendekati Markus. Mereka memperhatikan tamu-tamu itu. Salah seorang tamu mereka kenal. Dia adalah Perminas, Camat Malinau Selatan Hilir.
“Silakan masuk, Pak Camat,” kata Markus.
“Saya datang ke sini membawa tamu dari perusahaan sawit,” jawab Perminas.
Markus dan Piang saling bertatap. Keduanya bisa menduga maksud kedatangan camat dan tiga orang perusahaan sawit itu. Markus dan Piang mengajak warga sama-sama bertemu dan mendengarkan penjelasan orang-orang ini.
Sekitar 20-an warga datang. Mereka berkumpul di rumah Markus. Duduk membentuk lingkaran. Markus Ilun dan Piang Irang menjadi juru bicara.
Dari pertemuan itu, terungkap, tiga orang itu membawa bendera perusahaan sawit PT. Putra Bangun Bersama, PT. Dulong Agro Plantation, dan PT. Borneo Dulong Agro Lestari. Mereka mengincar hutan adat Dayak Punan Adiu.
“Kalau menanam sawit, masyarakat akan sejahtera,” kata salah satu dari mereka.
Perminas selaku wakil pemerintah menjelaskan, hanya mengantarkan orang-orang itu ke Kampung Dayak Punan. Dia telah mendapat izin bupati.
“Mohon maaf, bapak-bapak. Saya tidak bisa terima perusahaan sawit masuk di hutan kami,” kata Markus.
Perusahaan terus membujuk. Mereka mengiming-imingi kehidupan nyaman dan sejahtera. Perusahaan merinci, tahun pertama, target menanam sawit di hutan Dayak Punan seluas 40 hektar. Berikutnya 2015, target mereka 100 hektar, 2017 sebanyak 150 hektar, dan 2020 seluas 200 hektar.
“Biarpun masyarakat sejahtera, kayu di hutan kami habis dibabat,” kata Markus.
Markus tak goyah. Dia bersama warga menolak tawaran orang-orang perusahaan itu. Pertemuan berlangsung dari pukul 20.00 hingga 23.00 itu tak menghasilkan apa-apa. Rombongan pulang dengan tangan hampa. Malam itu, menjadi saksi penolakan warga Dayak Punan “mengusir” investasi sawit yang siap menghancurkan hutan adat mereka.
![Perkampungan desa Punan Adiu. Lokasinya di hutan Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau Selatan Hilir. Perusahaan kerap datang dan membujuk warga agar mereka boleh masuk ke hutan adat. Namun, warga desa ini sepakat mempertahankan sumber-sumber kehidupan mereka. Foto: Christopel Paino]()
Perkampungan desa Punan Adiu. Lokasinya di hutan Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau Selatan Hilir. Perusahaan kerap datang dan membujuk warga agar mereka boleh masuk ke hutan adat. Namun, warga desa ini sepakat mempertahankan sumber-sumber kehidupan mereka. Foto: Christopel Paino
***
Truk berukuran besar memuat batubara, lalu-lalang memecah kesunyian hutan. Jalan tak mulus. Penuh batu dan berlubang. Debu beterbangan menutupi pepohonan. Bak awan, debu ini menghalangi pemandangan saya.
Tak jauh dari jalan itu, dua perusahaan batubara beroperasi, PT Kayan Prima Utama Coal dan PT Bara Dinamika Muda Sukses.
Jalan ini menuju Desa Punan Adiu. Dari ibukota kabupaten menuju Punan Adiu ditempuh sekitar satu setengah jam. Sebelum pemekaran, daerah ini masuk Kalimantan Timur.
Punan adalah salah satu sub suku Dayak di Kalimantan. Diaspora etnis ini hingga ke negeri seberang di Serawak, Malaysia. Ia menyebar hingga di belahan Kalimantan.
Di Punan Adiu, mereka ada 27 keluarga dengan 121 jiwa. Luas pemukiman berkisar empat hektar dengan hutan adat seluas 17.400 hektar.
“Hutan ini tempat lahir kami,” kata Markus, pada medio Februari 2015.
Untuk bertahan dari godaan perusahaan, masyarakat Dayak Punan punya senjata. Senjata itu bukanlah bedil berisikan peluru tajam tetapi selembar peta. Peta yang menegaskan pengakuan tanah adat mereka di Adiu.
Peta itu dibuat partisipatif difasilitasi Lembaga Pemerhati Pendayagunaan Punan di Malinau (LP3M), dan Simpul Layanan Pemetaan Pertisipatif Kalimantan Timur (SLPP). Mereka bekerja sama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Pertisipatif (JKPP), dan Perkumpulan Padi Indonesia.
“Ketika Pak Camat dan tiga orang perusahaan itu datang, kami sedang proses pembuatan peta partisipatif,” kata Piang.
Piang Irang rajin mencatat. Ketika ada pertemuan dengan siapa saja, dia menjadi notulen. Detail-detail peristiwa dicatat. Dalam catatan Piang, di desa mereka seringkali datang orang survei batubara. Juga perusahaan hutan tanaman industri yang merayu warga menanam akasia. Perusahaan mengincar kayu log hutan adat.
“Sekarang dengan peta, masyarakat bisa menentukan sikap. Kami bisa menolak perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke hutan adat.”
Peta partisipatif masyarakat Punan Adiu baru selesai Januari 2015. Proses pembuatan memerlukan waktu panjang. Beberapa kali survei lapangan, dari Juni 2012 hingga 2014.
“Dalam peta ini tidak hanya bicara tata batas, juga tata ruang. Seperti di mana hutan adat, kebun, atau tempat warga berburu,” kata Ahmad Suudi Jawahir Asyami, Direktur Perkumpulan Padi Indonesia.
Bagi Among, panggilan akrab pria ini, peta adalah alat dan pengakuan diri masyarakat. Untuk pemerintah, katanya, sangat berguna karena dengan peta partisipatif akan tahu daerah itu ada masyarakat bermukim. Among berharap, peta itu bisa masuk rencana tata ruang wilayah.
![Hutan adat Dayak Punan Adiu, banyak diincar pemodal. Warga dirayu agar dapat mengubah menjadi sawit, HTi atau yang lain. Komunitas adat ini bertahan. Mereka bahkan komunitas adat kala pertama menyelesaikan peta wilayah di Malinau. Foto: Christopel Paino]()
Hutan adat Dayak Punan Adiu, banyak diincar pemodal. Warga dirayu agar dapat mengubah hutan ini menjadi sawit, HTi atau yang lain. Komunitas adat ini bertahan. Mereka bahkan komunitas adat kala pertama menyelesaikan peta wilayah di Malinau. Foto: Christopel Paino
Boro Suban Nicolaus, Direktur LP3M mengatakan, di Kabupaten Malinau, pemetaan partisipatif sudah mulai lama, diawali pelatihan pada 28 Februari 2012. Langkah maju juga tampak dengan ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.
“Pertama kali, peta partisipatif di Malinau yang jadi baru di Punan Adiu. Nanti peta milik ini akan menjadi model bagi kampung-kampung lain di Malinau,” kata Nico.
Menurut dia, proses awal pembuatan peta ini mengundang semua kampung-kampung tetangga, berjumlah enam desa. Mereka akan bertukar pendapat mengenai sejarah kampung, dan bersepakat tentang tata batas. Tujuannya, meminimalisir konflik, baik dengan perusahaan maupun sesama masyarakat.
Proses pembuatan peta ini, katanya, bukan tanpa kendala. Pernah dalam pembahasan peta terjadi selisih paham antara masyarakat Setarap dengan Punan Adiu dan Merap Gong Solok. Persoalannya Danau Sigong Kelapa. Luas 12 hektar. Orang Setarap ingin danau itu masuk wilayah mereka, tetapi berdasarkan sejarah itu wilayah adat Punan Adiu.
“Ketua adat dari Punan Adiu bilang, ‘tidak mungkin ikan danau dicat dan dibagi dua biar ketahuan punya masing-masing’. Lama berdebat, akhirnya mereka bersepakat danau itu masuk wilayah adat Punan Adiu dan menjadi titik temu tiga masyarakat adat. Tata batas berdasarkan sejarah nenek moyang mereka.”
“Orang-orang Dayak punya kesantunan adat yang luar biasa,” kata Nico.
Rahmat Sulaiman, Kepala Divisi Organisasi JKPP berharap, peta ini segera ditindaklanjuti ke level berikutnya, yaitu didaftarkan ke Badan Registrasi Wilayah Adat. Di kabupaten, katanya, aturan daerah itu harus ada turunan, yaitu peraturan bupati berisi pembentukan Badan Pelaksana Urusan Masyarakat Adat.
![Markus Ilun memperlihatkan pohon Gaharu di hutan adat.Foto: Christopel Paino]()
Markus Ilun memperlihatkan pohon Gaharu di hutan adat.Foto: Christopel Paino
***
Perahu ketinting melaju kencang melawan arus Sungai Malinau. Piang Irang memegang kemudi. Dia harus waspada. Kalau lengah, perahu bisa menghantam batu atau batang pohon besar di sungai. Kadang dia, memperlambat laju perahu. Sesekali mesin mati. Piang sigap turun dan mendorong perahu.
“Hutan adat orang Punan Adiu jauh dari sini. Kurang lebih setengah jam naik perahu,” katanya.
Pada 25 Februari 2015, saya dan beberapa wartawan bersama Piang Irang dan Markus Ilun dan warga lain ke hutan adat. Kami melewati beberapa anak sungai. Pohon-pohon rapat. Hutan lebat.
Markus turun pertama. Mengenakan kaos oblong lengan panjang bergaris merah hitam dan bercelana pendek.
“Ini pohon gaharu yang kami tanam.”
Markus memperlihatkan gaharu banyak tumbuh di sana. Sejak 2006, warga wajib menanam pohon dengan nama latin Aquilaria malaccensis ini di hutan mereka. Selain memiliki nilai tinggi, pohon ini menjadi tanda batas dengan wilayah hutan komunitas lain.
“Cara mengusir perusahaan juga dengan menanam gaharu. Perusahaan tidak bisa asal serobot karena tanda wilayah kami adalah pohon ini. Ini sudah ada di peta adat Dayak Punan Adiu,” kata Markus.
Gaharu juga memiliki hubungan erat dengan orang-orang Dayak Punan. Pohon ini memiliki nilai spiritual dan jadi ramuan obat-obatan. Dahulu, kata Markus, gaharu sebagai alat barter.
Di hutan ini juga diatur wilayah terlarang, tidak sembarang orang bisa masuk. Mereka juga membuat pos untuk mencegah orang mengambil kayu di hutan Punan Adiu.
“Kami sedang menggodok peraturan desa mengenai wilayah-wilayah adat yang dilarang maupun yang boleh beserta sanksi,” kata Piang.
Masyarakat Dayak di Punan Adiu memiliki kearifan lokal tinggi dalam menjaga wilayah adat. Namun, ancaman bisa datang kapan saja, terutama dari perusahaan.
“Kami tidak ingin menyerahkan hutan kami kepada perusahaan. Karena hutan ini tempat lahir kami.”
![Peta partisipatif yang telah rampung dibuat oleh masyarakat adat Dayak Punan Adiu. Mereka berharap, peta ini jadi 'senjata' mereka buat melindungi wilayah dan hutan adat. Foto: Christopel Paino]()
Peta partisipatif yang telah rampung dibuat oleh masyarakat adat Dayak Punan Adiu. Mereka berharap, peta ini jadi ‘senjata’ mereka buat melindungi wilayah dan hutan adat. Foto: Christopel Paino
Ketika Dayak Punan Siapkan “Senjata” Melawan Penghancuran Hutan Adat was first posted on March 9, 2015 at 11:44 pm.