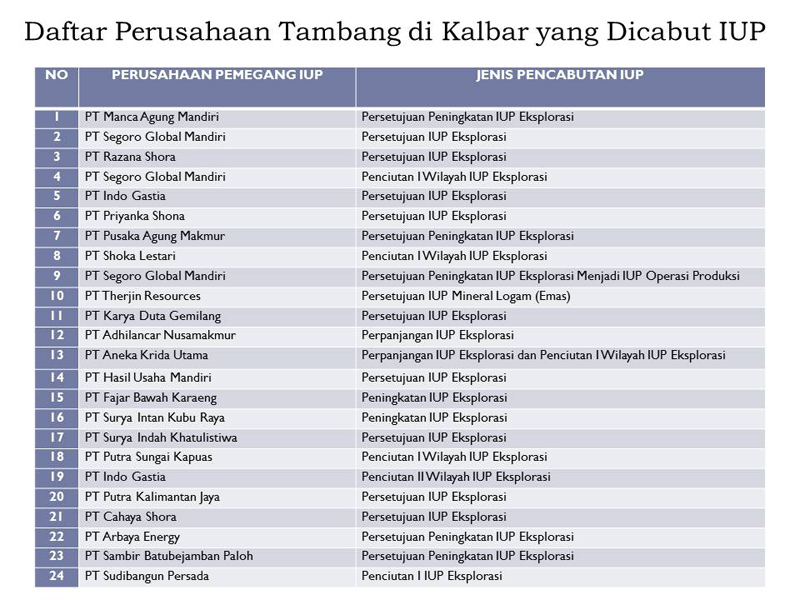Alat berat memuat kayu berkualitas bagus ke truk. Kayu ini hasil tebangan hutan Siosar untuk jalan menuju relokasi pengungsi. Akan dibawa ke manakah, kayu-kayu ini? Foto: Ayat S Karokaro
Pembangunan jalan buat relokasi para pengungsi korban Sinabung, hampir selesai 100%. Sejak pertengahan 2014, truk-truk besar dan kendaraan berat berada di hutan Siosar, Kecamatan Merek, membuat jalan ke relokasi pengungsi. Saat ini, 50 rumah korban Sinabung selesai dibangun.
Ada yang menarik dari pembuatan jalan relokasi ini, yakni, soal ribuan kubik batang kayu yang ditebang. Di hutan, suara kayu tumbang silih berganti. Setelah dipotong, kayu ukuran besar dimuat ke truk, dan dibawa keluar Siosar. Kemanakah kayu-kayu itu dibawa? Mongabay mencoba menelusuri, dan bertanya kepada pekerja dan penanggungjawab proyek pembuatan jalan itu.
Anto, mandor lapangan mengatakan, kayu tumbangan pembuatan jalan relokasi pengungsi sebagian buat perumahan Sinabung. Sebagian besar dijual dan dana buat pembangunan.
Apakah mendapat izin pihak terkait? Dia enggan berkomentar banyak dan menyarankan agar menanyakan kepada Bupati Karo, Terkelin Brahmana. Dia mengaku, lahan sudah ditebang, pada September 2014 sebanyak 10-15 hektar. Saat ini, lebih 20 hektar.
Ketika ditanya soal penimbunan jalan menggunakan kayu kecil yang tidak bagus, katanya, itu buat mempermudah kendaraan menebang dan perataan jalan, mengingat cuaca tidak menentu. Jika turun hujan, kendaraan tidak bisa bekerja maksimal, hingga menganggu pembuatan jalan ke relokasi pengungsi.
Kayu-kayu kecil buat menimbun jalan rusak parah ini sepanjang 500 meter. Sesuai kontrak, jalan dibuat hingga rumah baru pengungsi sepanjang dua sampai tiga kilometer.
Ketika Mongabay konfirmasi kepada Letkol Asep Sukarna, Komandan Satuan Tugas Tanggap Darurat Gunung Sinabung, Selasa (3/3/15), menyatakan, pembangunan jalan hampir selesai, dan segera diserahkan ke Pemerintah Karo.
Ketika ditanya soal kayu-kayu yang dibawa keluar dan dijual dia membantah. Katanya, kayu hanya buat fasilitas umum, sama sekali tidak ada dijual. “Kayu itu buat duduk-duduk dan dimanfaatkan masyarakat. Banyak patah dan rusak hingga tidak bisa lagi dipergunakan,” katanya.
“Siapa yang jual. Tidak benar itu. Kita ini menolong masyarakat, jangan dibesar-besarkan, dan ditanggapi. Jangan hanya karena satu dua orang, terus dibesar-besarin. Fokus saat ini relokasi selesai, dan segera diberikan pada masyarakat dan bisa hidup damai. Ada kepentingan lebih besar lagi saat ini,” ucap Asep. Namun dia akan mendalami informasi soal kayu yang dijual.
Dia menyatakan, rumah yang siap akan diserahkan ke pengungsi melalui pengundian, dan pembangunan terus berlanjut sampai selesai.
Relokasi bertahap kepada empat desa radius dinbawah tiga kilometer dari Sinabung, yaitu Desa Simacem, Desa Bekerah, Desa Sukamacem, dan Desa Kuta Tonggal.
Jhonson Tarigan, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, mengatakan, penetapan lokasi relokasi berdasarkan surat keputusan bupati, dan disetujui KLHK. Yaitu di Siosar, Kecamatan Merek. Disana ada agropolitan, semula untuk pemukiman dan pertanian. Ada lahan 450 hektar buat lahan pertanian korban Sinabung. Khusus lahan 450 hektar, masuk hutan Siosar, hingga mengajukan izin pinjam pakai dan sudah selama 20 tahun.

Kayu-kayu hasil tebangan buat jalan di hutan Siosar, yang setelah dipotong dimuat ke truk. Inikah yang kata Letkol Asep Sukarna kayu banyak patah dan rusak itu? Foto: Ayat S Karokaro
Kepada warga relokasi, mendapat perumahan 200 meter dengan rumah tipe 26. BPN, sudah mempersiapkan sertifikat.
Menurut dia, penggunaan kayu-kayu yang ditebang diawasi, sebagian besar buat pembangunan pengungsi Sinabung.
Dia membantah keterangan Anto yang menyebutkan kayu tebangan dibawa keluar buat keperluan relokasi. “Tidak benar itu. Semua sesuai peruntukan. Kita terus awasi kok.”
Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo, hanya memberikan izin pembangunan jalan sepanjang 3,8 kilometer dengan lebar 12 meter di Siosar. “Kita diperintahkan presiden mengerjakan dengan baik, teliti, dan tidak disimpangkan. Itu dijalankan.”
Peluang besar diselewengkan
Walhi Sumut menyikapi masalah ini. Kusnadi Oldani, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, menyatakan, wajar publik bertanya mengenai penyimpangan penebangan kayu di hutan Siosar. Pemerintah, katanya, tidak memberikan informasi terbuka soal nilai tegakan di hutan ini.
Sejak awal, pemerintah tak mengestimasi kasar soal berapa tegakan kayu dalam proyek pembuatan jalan ini.
Jika dari awal dilakukan, hal ini tidak menjadi tanda tanya besar atau kecurigaan. Dengan tak ada perkiraan tegakan kayu itu maka peluang penyelewengan terbuka lebar. Terlebih itu, kayu pinus yang berkualitas bagus. Rekam jejak penggunaan kayu tak ada.
“Upaya-upaya ini harusnya dibuka, hingga ada pengawasan dan tidak terjadi penyelewengan berakibat fatal bisa berujung pelanggaran hukum.”
Untuk itu, Walhi mendesak pengusutan soal ini. “Jangan jadi ada alasan demi pembangunan relokasi, lalu semena-mena di kawasan hutan. Itu salah besar. ”

Pembangunan rumah permanen buat para pengungsi Sinabung. Dari keterangan mandor lapangan, kayu hasil tebangan buat membangun rumah sebagian dan sebagian dijual. Foto: Ayat S Karokaro
Bangun Jalan dan Relokasi Pengungsi di Hutan Siosar, Kemana Kayu Hasil Tebangan? was first posted on March 4, 2015 at 3:36 pm.