Pernah mendengar nama hutan lindung? Itu biasa. Bagaimana dengan danau lindung? Tidak semua orang pastinya mengenal istilah ini. Maklum, di Kalimantan Barat, julukan ini baru populer di hulu Sungai Kapuas pada 2001 silam.
Ceritanya bermula dari sebuah hamparan danau seluas 124 hektar di Desa Nanga Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kuatnya kearifan lokal di desa itu telah mengantar sebuah terobosan baru di dunia konservasi.
Sebagai kawasan ekosistem rawa gambut air tawar, kondisi air di Danau Empangau cenderung gelap (coklat merah kehitaman). Penetrasi cahaya matahari ke dalam air sangat rendah. Ini menjadi penanda bahwa kawasan tersebut merupakan habitat asli siluk/arwana (Schlerofagus formosus).
Tak hanya arwana. Lebih dari 70 jenis ikan bernilai ekonomis seperti toman (Channa micropeltes), jelawat (Leptobarbus hoevani), ringau (Datnoides microlepis), tapah (Wallago leeri), dan belida (Notopterus borneensis) ada di danau itu.
Perjuangan menyelamatkan kawasan Empangau dimulai sebagai cita-cita beberapa tetua kampung sejak 1986. Berdasarkan catatan WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, saat itu sedang terjadi penangkapan ikan berlebihan (overfishing).
“Tidak hanya kawasan dan keragaman spesiesnya yang terancam. Sumber penghidupan masyarakat juga mulai menipis,” kata Anas Nashrullah, Community Empowerment Coordinator WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (19/3/2015).

Pemerintah Kapuas Hulu bersama warga Desa Nanga Empangau melepas induk ikan arwana di Danau Lindung Empangau. Foto: Dok WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat
Beranjak dari persoalan yang dihadapi itulah, kata Anas, beberapa warga mulai menunjukkan kepeduliannya dengan melepasliarkan seekor induk arwana di danau. Namun ini tak bisa langsung memenuhi harapan para tetua lantaran ketiadaan aturan yang mengikat semua warga desa.
Pada 1998, dengan melejitnya harga ikan arwana, digelarlah rapat rukun nelayan untuk menyusun aturan main nelayan dengan fokus melindungi Danau Empangau. Mulailah masyarakat menegakkan aturan nelayan dan hukum adat setempat.
Selanjutnya, tahun 2000 mereka membeli secara swadaya tiga ekor anak arwana untuk dilepasliarkan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengapresiasi niat baik masyarakat itu dan lahirlah SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2001 yang menetapkan 30 hektar dari total kawasan danau sebagai kawasan lindung berbasis pengetahuan dan kearifan lokal.
Sejak itu, kesehatan ekosistem masyarakat makin meningkat, seiring penguatan solidaritas sosial dan peningkatan sumber pendapatan maereka. Balai Riset Perikanan Perairan Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2009 mencatat, peningkatan kerapatan stok ikan saat musim hujan sebanyak 21.922 ekor per hektar. Ini jauh meningkat dari angka 12.000 ekor per hektar pada 2005.
Masyarakat Empangau telah mempraktikkan pembangunan berkelanjutan, jauh sebelum kenal konsep ini dari lokakarya. Mereka tak pernah menyangka hebatnya dampak upaya mereka bertahan hidup dan melindungi sumber penghidupan dan cara mengelolanya melalui penguatan hukum adat.
Pemerintah desa pun mendapat tambahan pemasukan. Misalnya alokasi dana solidaritas duka sebesar Rp 200 ribu per orang per tahun. Tata kelola pemerintah desa juga mendapat dukungan, baik pembiayaan organisasi pemuda dan perempuan, musyawarah kampung, maupun kegiatan olahraga.
Beberapa fasilitas sosial seperti jalan penghubung antarrumah yang terbuat dari kayu, jembatan, bangunan sekolah, rumah ibadah, bahkan honor guru disokong dengan sistem bagi hasil 10 persen dari pengelolaan Danau Lindung Empangau. Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan keberhasilan masyarakat ini melalui dua hal, yakni kelembagaan yang kuat serta aturan main yang jelas, tegas, dan tidak diskriminatif.
Puncak penghargaan pun datang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 16 November 2011 menobatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Danau Lindung Empangau sebagai Juara I Tingkat Nasional. Kesempatan ini membuka peluang bagi masyarakat di seluruh dunia untuk belajar bagaimana mengelola alam secara lestari. Anda tertantang?
Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio
Danau Lindung Ini Lahir dari Rahim Kearifan Masyarakat Empangau was first posted on March 21, 2015 at 1:02 am.





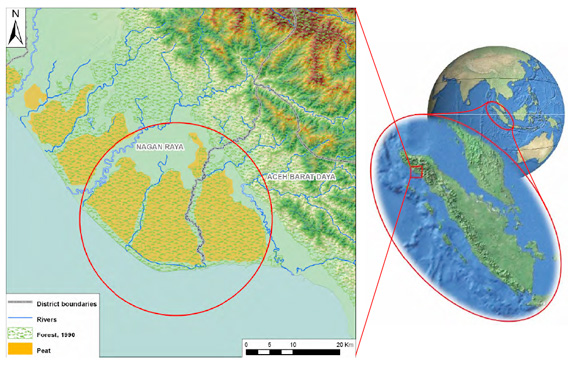































































 Akankah praktik-praktik seperti ini akan terus terjadi di perairan negeri ini? Foto: Australian National Fish Collection, CSIRO
Akankah praktik-praktik seperti ini akan terus terjadi di perairan negeri ini? Foto: Australian National Fish Collection, CSIRO