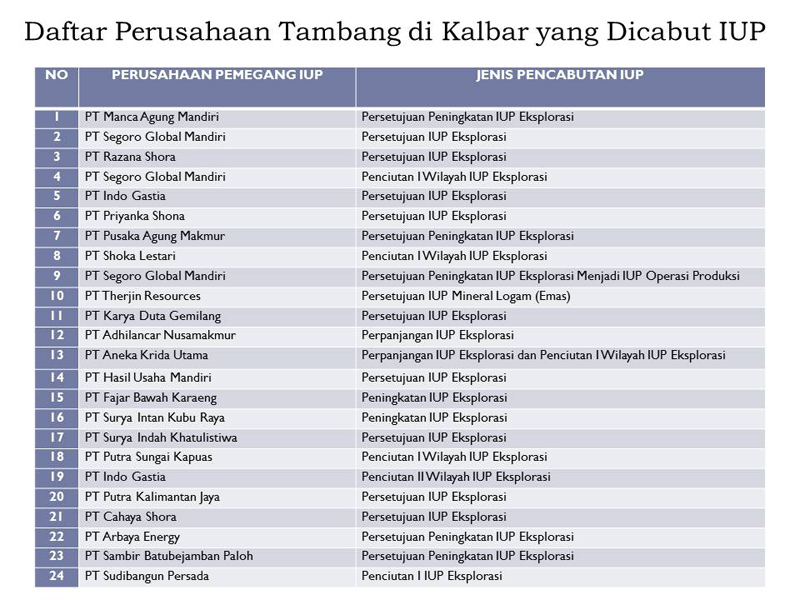Lahan yang sudah dibuka perusahaan sawit dan diputus beroperasi ilegal oleh Mahkamah Agung.Dengan penyatuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan serta peleburan BP REDD+ dan DNPI, berharap, hal-hal seperti ini bisa dihentikan dan tata kelola hutan hutan menjadi lebih baik. Bukan sebaliknya. Foto: Save Our Borneo
Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan BP REDD+ sudah lebur ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak keluar peraturan Presiden 21 Januari 2015. Sebagian kalangan mengapresiasi, ada juga menyayangkan. Mereka menilai, peleburan memiliki hal positif, tetapi juga tantangan besar.
Heru Prasetyo, mantan Kepala BP REDD + mengatakan, risiko peleburan kemungkinan ada kegiatan BP REDD+ tidak berlanjut. Sebab, lembaga baru ini tidak mempunyai tupoksi mencakup hal-hal yang dilakukan BP REDD+.
“Peluangnya, Menteri LHK bisa bekerjasama dengan menteri-menteri lain lebih baik lagi. Namun, mungkin ada pelimpahan kewenangan kepada Menteri Luar Negeri untuk urusan hubungan internasional,” katanya dalam pelatihan REDD+ di Jakarta, awal Maret 2015. Jika itu terjadi, kata Heru, akan kembali ke bisnis seperti biasa. Meskipun struktur baru, tetapi timbul risiko hilang koordinasi.
Dia menilai, kebingungan provinsi dan kabupaten bisa lebih banyak lagi. Selama ini, BP REDD+ biasa mengkomunikasikan lintas kementerian.
Menteri LHK, katanya, sudah mengajak Menteri Agraria dan Pertanian bekerjasama. Inisiatif berkoordinasi lintas sektoral sudah ada, tinggal menunggu implementasi.
“Posisi dirjen akan dilelang. Ada waktu tiga bulan. Dirjen baru ini bisa mengajukan anggaran dalam empat bulan. Artinya, selama tujuh bulan tidak beraktivitas di KLHK soal REDD+.Tetapi kita berikan semangat mudah-mudahan tahun depan sudah jalan.”
Kesempatan lain, aktivis Debwatch Indonesia Arimbi Heroepoetri menggatakan, peleburan adalah sebuah keniscayaan. “Sebaiknya isu perubahan iklim dikelola lembaga yang tidak sektoral apalagi non departemen. Perasaan kita senang, tapi harap-harap cemas,” katanya dalam diskusi di Jakarta.
Menurut dia, peleburan baik tetapi jika dengan persyaratan ketat, misal perlu pendekatan multisektor. Sebab, isu perubahan iklim tidak hanya soal hutan, juga non hutan.
“Isu maritim belum terjangkau. Harus ada lembaga multisektor. Sistem tata negara perlu dirombak. Ide kita, lembaga itu langsung di bawah presiden. Kita tahu, banyak kementerian dan lembaga tidak efektif. Birokrasi lamban.”
Peleburan lembaga, katanya, juga harus memastikan agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim beejalan cepat. “Peleburan baik tetapi orang-orangnya sama. Selama ini, Kementerian Kehutanan diisi orang yang kulturnya menikmati kerajaan bisnis perizinan. Harus diubah.”
Sisilia Nurmala Dewi dari HuMa mengapresiasi keputusan Presiden melebur empat lembaga (Kemenhut, Lingkungan Hidup, BP REDD+ dan DNPI) menjadi satu. Meski ada berbagai tantangan besar.
“Konsekuensi ada ketidakstabilan institusi. Visi misi, orang-orang dan program kerja yang selama ini terpisah sekarang digabung,” katanya.

Berharap, perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan makin baik dengan peleburan BP REDD+ dan DNPI ke Kementerian LHK. Foto: Sapariah Saturi
Dia berharap, peleburan lembaga ini, model pembangunan bisa diperbaiki. KLHK, ujar dia, harus bisa mengarusutamakan isu perubahan iklim dalam konsep pembangunan. “Dengan digabungkan dalam satu dirjen tentu ada garis pertanggungjawaban jelas. Tetapi ada persoalan menyangkut kinerja. Harus luas. Kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lain harus terjalin.”
Muhammad Djauhari dari Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyaratan ikut bersuara. Menurut dia, langkah pemerintah melebur lembaga sudah tepat. “Pembiayaan dan koordinasi lebih mudah. Dulu dengan BP REDD+ dan DNPI, masing-masing sektor harus menyetorkan orang. Kemenhut setor orang ke DNPI dan REDD+ begitupun KLH.”
Yuyun Indardi, dari Greenpeace Indonesia mengatakan, dalam konteks menyederhanakan birokrasi penggabungan lembaga ini berhasil. “Tetapi kalau berbicara soal perubahan iklim, bukan hanya tanggungjawab KLHK. Kementan, ESDM dan kementrian lain yang berhubungan dengan eksploitasi SDA juga punya andil. Itu jadi tantangan lintas sektor.”
Untuk itu, dia pernah mendorong ada Kementerian SDA atau kementerian koordinator yang menangani masalah ini. Hingga, kebijakan di Kementan, ESDM dan kementerian lain bisa sinkron dengan upaya kelestarian lingkungan.
M. Kosar dari Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan, dulu BP REDD+ lemah karena tidak bisa mendorong kementerian sektoral bertindak. Setelah lebur, juga masih banyak tantangan. “Tantangan karena orangnya sama. Kita berpikir bagaimana agar antarlembaga bisa saling mempengaruhi.”
Temuan FWI, ada 41 juta hektar kawasan hutan berstatus lindung, produksi dan alokasi penggunaan lain tidak ada pengelola. “Dengan peleburan ini, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan hutan yang tidak ada pengelola. Pemerintah harus bisa menyelesaikan semua konflik.”
Sedangkan Raynaldo Sembiring dari Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) menyatakan, penggabungan ini harus diikuti upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis. Dimulai dari aspek perencanaan sampai penegakan hukum.
“UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan harus menjadi dasar tugas KLHK, terutama untuk mengerem pemberian izin eksploitasi yang masif oleh Kemenhut.”
Menurut dia, paling mendesak adalah penuntasan mandat penyelesaian rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (RPPLH) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kedua hal ini demi memberikan arahan jelas tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berbagai sektor. “Ketika RPPLH dimuat dalam RPJM, moratorium bisa disitu. Lintas sektor. KLHS jadi instrumen penting.”
Ke depan, katanya, dalam pembuatan RPPLH dan KLHS, KLHK harus berpegang teguh pada UU Lingkungan Hidup. “Penggabungan ini saling melengkapi. Kemenhut kuat di daerah, dan KLH jadi punya power,” katanya.
Di lain kesempatan, Andreas Lagimpu, Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional utusan Kamar Masyarakat Regio Sulawesi mengatakan, penggabungan kelembagaan di KLHK harus berjalan efektif, tanpa terhambat permasalahan teknis. “Jangan sampai penggabungan justru menghambat kinerja KLHK,” katanya.
Menurut dia, political will KLHK belum berujung aksi nyata. Terlalu banyak peraturan dikeluarkan kementerian ini, namun implementasi belum terlihat.
Andreas menilai, salah satu ukuran implementasi peraturan-peraturan belum terlihat adalah putusan Mahkamah Konstitusi soal masyarakat adat belum berjalan nyata.
Berikut Peluang dan Tantangan Peleburan BP REDD+ dan DNPI was first posted on March 24, 2015 at 10:40 pm.