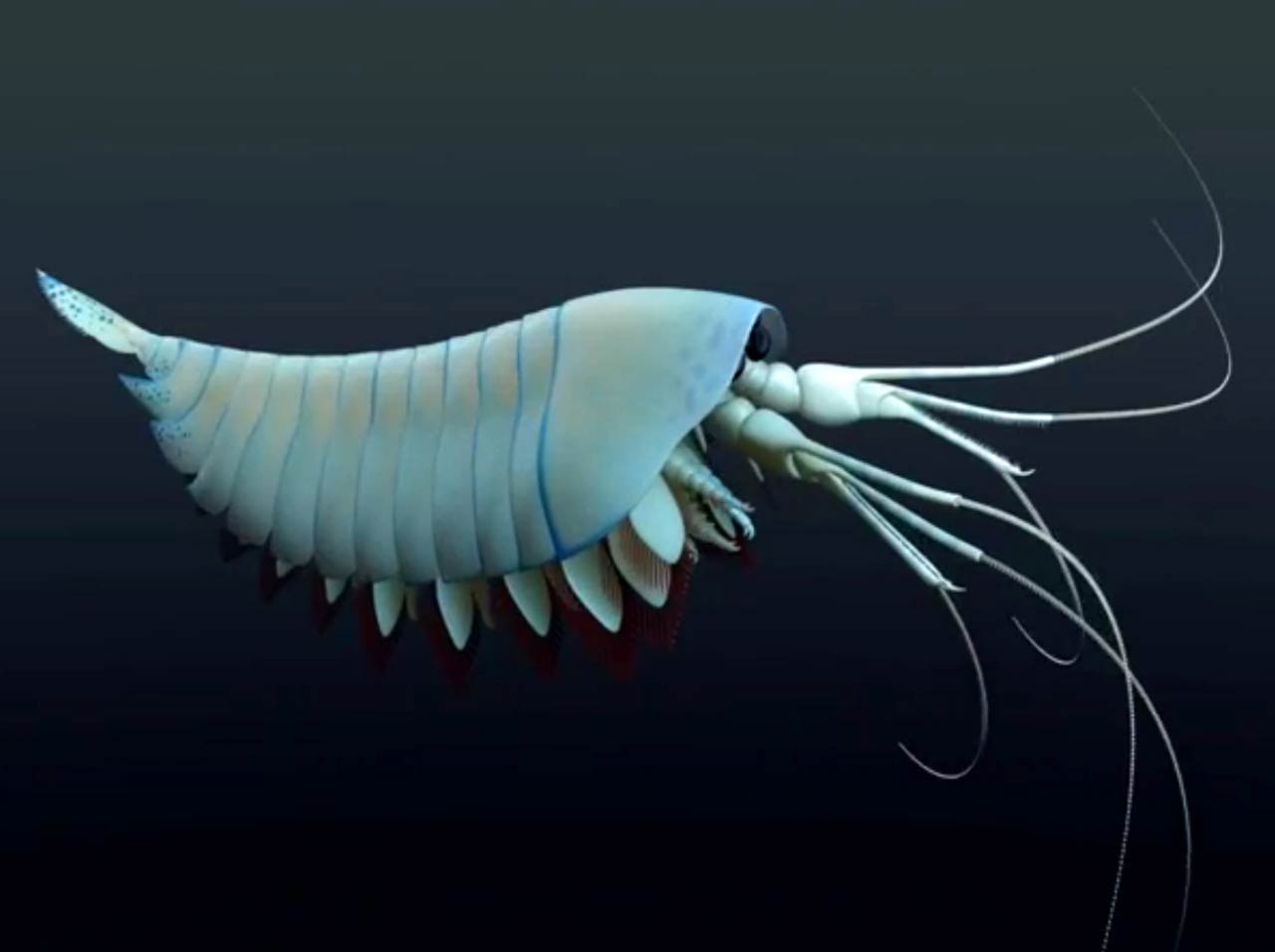Kampanye penghematan energi Earth Hour yang digagas oleh WWF, kembali digelar serentak pada Sabtu (28/03/2015) di seluruh dunia. Di Indonesia, tercatat ada 30 kota dan puluhan komunitas yang ikut berpartisipasi memadamkan lampur selama sejam pada pukul 20.30 – 21.30.
Akan tetapi, beban pemakaian listrik selama sejam pelaksanaan Earth Hour justru sedikit naik. Hanya beberapa daerah seperti Jakarta, Jawa Barat dan beberapa kota lain yang bebannya turun kecil.
![Pelaksanaan Earth Hour tahun 2014 di Bundaran HI Jakarta. Foto : WWF-Indonesia]()
Pelaksanaan Earth Hour tahun 2014 di Bundaran HI Jakarta. Foto : WWF-Indonesia
Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto menduga hal tersebut dipengaruhi faktor cuaca, dimana pada saat perayaan Earth Hour di beberapa daerah cuaca cukup panas sehingga mendorong orang untuk menyalakan pendingin udara (AC). Hal ini juga mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat untuk mengikuti program ini masih relatif rendah.
PLN mencatat, beban listrik Jakarta pada Sabtu 28 Maret 2015 jam 21.00 WIB sebesar 3.322 Mega Watt (MW) atau turun 165 MW (4.73 %) dibanding beban pada hari Sabtu 14 Maret 2015 pada jam yang sama yang sebesar 3.487 MW. Sementara beban listrik di Jawa Barat tadi malam jam 21.00 WIB sebesar 4.072 MW atau turun 19 MW (0.22 %) dibanding beban pada 14/3 jam yang sama yang sebesar 4.091 MW.
“Di sistem kelistrikan Jawa Madura Bali (Jamali) tadi malam beban justru cenderung naik,” kata Bambang seperti dikutip dari laman PLN. Beban Jamali 28 Maret 2015 jam 21.00 WIB sebesar 19.680 Mega Watt (MW) atau naik 385 MW (1.99 %) dibanding beban pada jam yang sama Sabtu 14/3 yang sebesar 19.295 MW.
Pada perayaan earth hour 2014, beban listrik di Jamali turun sebesar 509 MW. Sementara beban listrik di Sumatera pada 28 Maret 2015 jam 21.00 WIB sebesar 4.218 MW atau naik 34 MW (1.52 %) dibanding beban pada jam yang sama 14/3 yang sebesar 4.184 MW. Perbandingan sengaja dengan beban pada hari yang sama dua minggu lalu karena pada Sabtu 21 Maret 2015 ada perayaan Nyepi yang juga mempengaruhi beban listrik.
Gerakan Berkembang
Direktur Program Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga mengatakan pelaksanaan kampanye Earth Hour berkembang dari tahun ke tahun dengan makin banyak pemerintah daerah dan terutama komunitas yang terlibat. “Earth Hour di Indonesia berkembang pesat. Ada 30 kota yang melakukan secara mandiri. WWF hanya membantu dan mengarahkan saja,” katanya.
30 kota yang terlibat antara lain mulai dari Aceh, Padang, Lampung, Jakarta, Bekasi, Tangeran, Bandung, Jogja, Solo, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Denpasar, Pontianak, Makassar sampai ke Jayapura.
![Pelaksanaan Earth Hour tahun 2014 di Jakarta. Foto : WWF-Indonesia/Nefa D Firman]()
Pelaksanaan Earth Hour tahun 2014 di Jakarta. Foto : WWF-Indonesia/Nefa D Firman
Nyoman mengatakan kegiatan Earth Hour memang berbasis di perkotaan, dengan kampanye utama berupa gaya hidup hemat energi setiap waktu. Kampanye Earth Hour difokuskan di Jawa Bali dan terutama di Jakarta, karena 78 persen konsumsi listrik Indonesia terfokus di Jawa – Bali karena 68 persen konsumennya berada di pulau tersebut. Sedangkan Jakarta dan Tangerang menyerap 23 persen dari konsumsi listrik Indonesia.
Diilustrasikan bahwa pelaksanaan satu jam Earth Hour oleh 10 persen penduduk Jakarta atau 700 ribu rumah mematikan 2 lampu selama 1 jam, akan menghemat 300 MW atau cukup untuk mengistirahatkan 1 pembangkit listrik, setara dengan listrik untuk menyalakan 900 desa, mengurangi beban biaya listrik Jakarta ± Rp 200 juta, mengurangi emisi ± 267 ton CO2, setara dengan daya serap emisi dari 267 pohon berusia 20 tahun dan setara dengan ketersediaan oksigen untuk ± 534 orang.
Selain kampanye penghematan energi, WWF Indonesia membebaskan komunitas pelaksana Earth Hour menambahkan materi kampanye sesuai kondisi daerah masing-masing. “Komunitas-komunitas itu juga menginisiasi kampanye konservasi. Kita juga dorong agar berkontribusi dalam program konservasi WWF,” ujarnya.
Untuk Earth Hour 2015 yang bertema “Hijaukan Hutan, Birukan Laut”, WWF Indonesia mengusung 7 isu kampanye konservasi yaitu laut dan pesisir, deforestasi, biodiversity, sampah, sungai & air, transportasi, dan energi. Ada tiga fokus proyek adopsi yaitu mangrove, koral, dan penyu.
Kehilangan Substansi
Mantan Direktur Energi dan Iklim WWF-Indonesia, Fitrian Ardiansyah mengatakan apapun kegiatan yang meminta masyarakat, pemimpin dunia dan negara untuk mengingatkan perlunya pengelolaan lingkungan dan bumi lebih baik, mitigasi dan reduksi perubahan iklim tetap diperlukan dan harus didukung.
“Earth Hour merupakan salah satu bentuk kegiatan itu. Ini seperti peringatan Hari Bumi, yang menjadi simbol untuk mengingatkan kita semua. Sama seperti perayaan hari-hari besar keagamaan,” katanya.
Tetapi apakah kegiatan Earth Hour sudah benar-benar mengingatkan semua pihak untuk bergaya hidup hemat energi? Fitrian mengatakan ada tantangan besar dalam pelaksanaan kegiatan menyangkut kapasitas organisasi sebesar WWF, bahkan yang dilakukan oleh PBB sekalipun.
“Apa yang ingin dicapai dari Earth Hour? Bila target kepada masyarakat luas dan komunitas, maka pemimpin daerah, tokoh keagamaan, tokoh masyarakat dan pemimpin komunitas harus dilibatkan, seperti melibatkan komunitas pejalan kaki, komunitas bike to work, komunitas pelari, dan sebagainya,” kata salah satu penggagas Earth Hour di Indonesia itu.
Dia melihat karakter masyarakat Indonesia yang tidak lepas dari patron pemimpinnya, artinya masyarakat akan lebih melihat dan mengerjakan apa yang diharapkan bila pemimpinnya pun ikut andil dalam kegiatan tersebut.
“Ada kesenjangan pada jargon dan kebijakan pengelolaan lingkungan dan ekonomi di pemerintahan dan perkotaan. Jargon ini harus seiring dengan platform pembangunan dan politik di nasional, provinsi, dan kota,” katanya.
Dia melihat Earth Hour 2015 juga terlalu banyak dibebani oleh isu yang ingin diangkat. Ada 6 isu konservasi selain isu utama tentang energi pada program kampanye tahunan WWF itu.
“Kalau kegiatan banyak terbebani banyak misi, masyarakat akan sulit menangkap dan mencerna. Kalau kampanye itu ingin meminta perubahan kebijakan ke pemerintah, pemerintah juga akan bingung karena terlalu banyak permintaan,” katanya.
Lebih baik Earth Hour dikembalikan pada misi awal yaitu tentang penghematan energi dengan kemasan kegiatan yang tuntas, tegas tapi ringkas.
Fitrian juga melihat ada kecenderungan kegiatan Earth Hour dari tahun ke tahun semakin terasa menjadi hanya sekedar seremoni. “Seperti layaknya suatu event, ada kecenderungan bisa terjebak dalam seremoni, kalau kegiatan tidak digawangi oleh tim yang kuat dengan substansi kegiatan,” katanya.
Meskipun begitu, kegiatan kampanye semacam Earth Hour ini masih kurang dan perlu diperbanyak lagi. “Event untuk mengingatkan pengelolaan bumi dan linkgungan masih kurang, tapi jangan sampai terjebak dalam rangkaian seremonal yang kehilangan subastansi, acara seharusnya mudah dicerna dan tataran audien,” jelasnya.
Dia melihat enam tahun pelaksanaan Earth Houar di Indonesia, semestinya substansi kampanye sudah semakin jelas. “Harusnya sudah jelas (substansi kampanye), mau minta apa ke Presiden, ke menteri minta apa dan ke pemda minta apa. Perubahan apa yang kita ingin lihat. Harusnya tidak dipisah antara komunitas dan pemimpin komunitas dan pemerintah,” katanya.
Masyarakat atau komunitas bakal berubah karena sebagai makhluk sosial tentu juga ingin berbuat baik. Apalagi kalau ada keuntungan atau insentif dari pemerintah untuk mendorong perubahan itu.
![Konfigurasi Earth Hour saat melintas di Jl. Jenderal Sudirman Jakarta, 17 Maret 2013 silam. Foto: Irwan Citrajaya/Earth Hour Indonesia]()
Konfigurasi Earth Hour saat melintas di Jl. Jenderal Sudirman Jakarta, 17 Maret 2013 silam. Foto: Irwan Citrajaya/Earth Hour Indonesia
“Ada hubungan dengan perubahan perilaku masyarakat dengan perubahan perilaku di pemerintahan. Misalnya program pengurangan sampah, mendaur ulang sampah akan berhasil bila masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari program itu, misalnya ada keuntungan ekonomi atau ada pengurangan pembayaran,” jelasnya.
Oleh karena itu, Fitrian mengharapkan adanya substansi kampanye yang jelas, terukur dan sederhana dalam pelaksanan Earth Hour di masa mendatang, agar perubahan yang diinginkanpun seperti gaya hidup hemat energi bisa tercapai.
Fokus Kampanye Energi
Sedangkan pengamat energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mengatakan Earth Hourmerupakan inisiatif kampanye yang baik untuk mengajak orang memahami konsekuensi penggunaan energi terhadap lingkungan, yaitu dalam bentuk perubahan iklim.
“Dengan demikian mengurangi penggunaan listrik untuk waktu tertentu bisa membantu mengurangi kebutuhan listrik. Sejam hanya sebagai contoh, tetapi tujuannya diharapkan bisa menjadi kebiasaan menggunakan energi yang efektif dan efisien,” katanya.
Fabby melihat pelaksanaan Earth Hour di masa mendatang agar fokus pada kampanye efisiensi energi, tanpa ditambahi isu kampanye lainnya, sehingga pesan yang ingin disampaikan tersampaikan secara jelas kepada masyarakat luas.
“Pesan dari kampanye kepada pengguna listrik tidak sampai. Kita lihat, acara lebih cenderung seremonial, dengan melibatkan artis dan perusahaan, kurang menyasar ke masyarakat,” tambahnya.
Senada dengan Fitrian dan Fabby, Kepala Sekolah Thamrin School Farhan Helmy mengatakan gerakan Earth Hour seharusnya bisa menjadi kampanye yang efektif dan serius dalam konservasi dan efisiensi energi.
“Diharapkan gerakan ini menjadi lebih masif dengan dipimpin oleh pemerintah. Misalnya ada kebijakan dan praktek efisiensi energi yang signifikan pada gedung-gedung pemerintahan, baik pada level nasional maupun di kota-kota,” kata penggagas Green Voice Indonesia itu.
Pemerintah bisa mendorong program efisiensi energi dengan mengeluarkan standar pemakaian perangkat elektronik yang hemat energi kepada seluruh instansi pemerintah. Apalagi sesuai dengan hasil penelitian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) bahwa biaya energi dengan tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi berasal dari dua hal utama yaitu dari penggunaan dan alih fungsi lahan (land use land use change forestry/LULUCF) dan di luar sektor LULUCF, termasuk energi.
“Maka pesan Earth Hour menjadi tepat untuk efisiensi energi. Bahkan sekarang ada momentum yang tepat untuk penghematan energi yaitu harga minyak global yang meningkat. Oleh karena itu, pesan kegiatan Earth Hour lebih baik fokus pada soal energi saja,”tambah mantan Koordinator Pokja Mitigasi Perubahan Iklim DNPI itu.
Kampanye Earth Hour 2015 Makin Meluas, Tapi Makin Kehilangan Substansinya. Kenapa? was first posted on March 30, 2015 at 5:58 am.